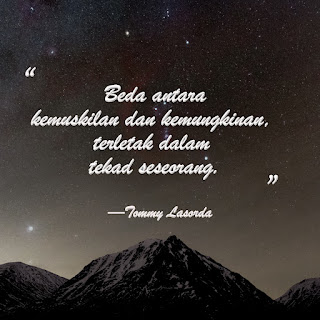"Kurasa, engkau pernah mendengar cerita ini,” Rembulan membuka pembicaraan setelah mengucapkan Basmalah dan Salam. "Ingat cerita tentang 'The Pied Piper,' film animasi pendek yang diproduksi oleh Walt Disney? Jadi, aku akan menyampaikan padamu, sebuah re-make dari legenda Jerman ini.
Konon, lebih dari lima ratus tahun yang lalu, tersebutlah Kota Hamelin di Brunswick, kota pelabuhan yang makmur. Aliran sungai Weser yang dalam dan lebar di sisi Selatan, menyapu dindingnya, menjadikannya tempat yang paling menyenangkan, yang belum pernah engkau saksikan. Tongkang penuh jagung, melintasi Sungai Weser dan bongkar-muat di Hemelin. Dengan gudang yang penuh jagung dan gandum, muncullah pabrik penggilingan jagung dan gandum, toko roti, yang memanggang roti dan kue, toko yang menjaja roti dan kue, dan, tentu saja, menjadi penganan warganya.
Saking makmurnya warga kota tersebut, dan sibuk bongkar-muat, menggiling, memanggang dan makan, mereka tak mengacuhkan segala buangan dan sampah, menumpuk di jalan. Dan tentu saja, adanya sampah, datanglah para Tikus, yang bertandang dan menetap..
Para tuan dan nyonya Tikus ini, membawa petaka besar. Mereka melawan anjing dan mematikan peran para kucing, menggigit bayi dalam buaian, memakan keju dalam drum, dan bahkan menjilat sup langsung dari sendok para juru-masak. Mereka membuka botol-botol yang berisi asinan, membuat sarang di dalam topi, dan mengganggu pula obrolan emak-emak, menenggelamkan cettingan mereka, dengan ciutan dan cicitan, dalam beragam cara yang menjengkelkan.
Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Para warga berduyun-duyun ke Balai Kota, dan mengetuk gerbang kuningan Balai Kota, menggelar demo, buat ngepoin, apa sih yang dapat dilakukan Pak Walikota terhadap tikus-tikus tersebut. 'Ini jelas,' teriak mereka, 'Pak Wali, doo-ngok, dan para Konco-konconya, ter-laa-luu! Tak bisa mikir, padahal mereka telah membeli mantel berlapis bulu cerpelai, pakai duit kita, namun tetap dungu, lantaran tak bisa atau tak mau memutuskan, cara terbaik mengeluarkan kita dari malapetaka ini! Jangan kira, karena sudah tua dan gendut, mudah menemukannya dalam mantel berbulu? Bangunlah, tuan-tuan! Peraslah otakmu, demi menemukan penawar yang tak kami punyai, atau, sesuai takdir, kami akan membantumu berkemas-kemas!'
Mendengar ini, Pak Walkot dan para Kroninya, bagai bebek di timpuk batu, 'Kwek!'—tersentak, kaget. Selama satu jam mereka duduk rapat. Akhirnya, Pak Wali memecah keheningan, 'Sebagai jalan pintas, aku akan menjual mantel-buluku seharga satu Gulden! Sangat mudah menebak tekanan yang terjadi pada kepala seseorang, sebab aku merasa, kepalaku yang malang ini, menuai sakit. Aku telah membuat sketsa, dan semuanya sia-sia, cuma karena mencari jebakan, jebakan, dan jebakan!'
Saat ia mengatakan ini, terjadi secara kebetulan, ketukan lembut, terdengar dari pintu ruang-rapat. 'E copot,' latah Pak Wali, 'Apa itu?' Semuanya, tampak boncel, walaupun gemuknya minta ampun, matanya, tak cerah pula, atau lebih lembab dari tiram yang terlalu lama terbuka, kecuali pada siang hari, perutnya memberontak, minta sajen sepiring kura-kura hijau yang lekap, 'Walau semata gesekan sepatu di karpet, atau apapun yang mirip suara tikus, membuat jantungku deg-degan!'
'Maaasuuuwk!'—teriak Pak Walkot, ia tampak agak bergaduk. Dan masuklah sosok yang teramat eksentrik, dengan mantel panjang fenomenal, mulai tumit hingga kepala, separuh kuning dan separuh merah, dan bertubuh tinggi-kurus, dengan mata biru tajam, masing-masing bak peniti, rambut lurus nan tipis, namun kulit kehitaman. Tiada jambang di pipi ataupun janggut di dagu, namun di bibir, senyumnya bagai terminal keluar-masuk mikrolet. Tak ada yang dapat menebak keluarga dan kerabatnya, tak ada yang bisa diam mengagumi sang lelaki jangkung dan pakaiannya yang baheula. 'Mirip kakek buyutku, setelah mendengarkan suara Sangkakala, berjalan dengan liar dari batu nisannya, yang diwarnai!' kata salah seorang dari mereka.
Ia bergerak maju ke meja rapat dan berkata, 'Yang Mulia. Aku bisa, dengan pesona gaibku, menarik segala macam makhluk, yang hidup di bawah matahari, yang merayap atau berenang atau terbang atau berlari, agar mengikutiku, dengan cara yang belum pernah engkau saksikan! Dan aku menggunakan pencitraanku, pada makhluk yang menyengsarakan manusia, tikus mondok, cebong dan kodok, bunglon dan tokek, serta ular beludak. Orang-orang menyebutku, Peniup Seruling Anekawarna. Syarat dan ketentuan berlaku, aji-aji pemukauku ini, takkan mempan terhadap segala jenis KADRUN.'
Dan setelah itu, mereka melihat di lehernya, syal bergaris merah dan kuning, senada dengan mantelnya. Dan di penghabisan syalnya, tergantung seruling, mereka melihat jemarinya selalu bergerak-gelisah, seolah tak sabar memainkan suling. Di atas seruling ini, ada taring tua, menjuntai, di atas mantelnya.
'Ya,' katanya, 'Aku peniup seruling yang miskin. Juni lalu di Tartar, aku membebaskan orang Campa, dari kawanan besar agas. Di Asia, aku mengejar Nizam dari sekumpulan kelelawar vampir yang menyeramkan. Adapun Tikus, perhatikan cerita berikut ini,
Para Tikus, sebenarnya tak suka keju, mereka makan keju lantaran nyaman, bukan karena mereka menyukainya. Tikus cenderung lebih menyukai makanan yang berkadar-gula. Keju terdiri dari protein, yang biasanya, tak manis. Itulah sebabnya, para Tikus akan lebih mudah tertangkap-tangan dalam perangkap, yang diberi umpan secuil cokelat, dibanding sebongkah keju.
Cerita ini, bermula dengan dengan sebuah pertanyaan lain, 'Jika para Lebah mampu mengurus pemerintahan, mengapa tidak para Tikus, yang berotak hebat namun tak berisi, dan yang berkekuatan lebih dahsyat, dengan ajaran Aksioma-aksioma Machiavelli, sanggup pula mengurus pemerintahan?
Dan demikianlah, akhir-akhir ini terjadi, di Negara Demokrasi Republik Tikus. Sang raja telah menemukan bongkahan Keju Cheshire yang menakjubkan, dimana para menteri negaranya, dapat hidup dalam keberlimpahan dan tumbuh membesar.
Sebuah partai kuat, langsung bergabung, dan mereka bersatu dalam sebuah kekuatan, agar gagasan-gagasan mereka, dapat diterapkan, karena katanya, tiada yang lebih setia dan sepatriot mereka, yang mendukung Negara, dan juga Istana.
Tak lama setelah para Bangsawan ini, diterima, segala kebajikan hebat itu, sirna. Mereka, dengan cara tercepat, merancang, agar dapat membesarkan diri-sendiri dan keluarga mereka. Para politisi, cenderung mencari terlebih dahulu, keuntungan demi diri-sendiri.
Partai lain, mengamati dengan baik, bahwa mereka itu, dimanjakan, padahal mereka sendiri, kelaparan. Merekapun menjebak para menteri dengan kehinaan, mengusir mereka dan mengambil-alih posisinya. Inilah prinsip-prinsip yang adil, yang dikenal sebagai para pendukung sejati Istana.
Adapun bila menyinggung persoalan Demokrasi, mereka akan mati-matian mempertahankannya; namun tetap berada dalam posisi mereka, tak pedulikan negara dan bangsa. Sama seperti yang lain, semua keterampilan mereka itu, semata agar bagaimana dapat mengisi penuh perut mereka. Mencermati perkembangan ini, seekor Tikus yang tak buta-buta amat dalam intrik negara seperti manusia, tetapi lebih terhormat, menjawab, 'Dari setiap sisi, kalian ini, membingungkan. Segala perdebatanmu cuma berkisar di seputaran ini: para politisi, siap mencari cara, agar terlebih dahulu, memperoleh Keju.'
Saat ini, lebih banyak makanan yang mudah diakses. Itu berarti, para tikus lebih cenderung mengejar hal-hal yang mereka sukai, seperti gula dan biji-bijian. Dan engkau tahu kaan apa maksudnya?
'Jika aku bisa membersihkan Kotamu dari para Tikus,' lanjut sang Peniup seruling, 'Maukah engkau membayarku seribu gulden?'
'Satu ribu? Nehi, lima puluh ribuh!' sahut Pak Walkot dan rekan, dalam ketertakjuban.
Sang Peniup seruling melangkah ke jalanan, dengan senyum mungil, seolah-olah ia tahu, sihir apa yang terlelap senyampang di dalam pipanya yang keren. Lalu, ia memonyongkan bibirnya, bagai pedangdut kondang, meniup sulingnya. Matanya yang tajam berkelap-kelip, berwarna hijau dan biru, laksana nyala lilin bertabur garam. Dan sebelum tiga nada lengking sang pipa siulkan, engkau 'kan mendengarnya kayak gerutuan seorang serdadu. Dari gerutuan membesar jadi omelan, dari omelan jadi gemuruh yang dahsyat, dari rumah-rumah, para Tikus datang bergaduh. Tikus besar, tikus kecil, tikus kurus, dan tikus berotot. Tikus coklat, tikus hitam, tikus abu-abu, dan tikus kuning. Tikus yang sudah bau tanah, berjalan tertatih, dengan langkah berat perlahan, tikus yang masih bau-kencur dan muda-belia nan galaw, berjalan seraya menari-nari, endut-endutan.
Bapak, ibu, pakde, poro sederek sedulur, melambaikan ekor dan sungutkan misai. Puluhan dan lusinan keluarga tikus, kang-mas, mbak-yu, bojo, bini—mengikuti sang Peniup suling demi hidup mereka. Melangkah maju dari jalan ke jalan, ia memainkan seruling, dan langkah demi langkah, para tikus mengikutinya sambil goyang ngebor, goyang ngecor, goyang patah-patah, goyang gergaji, goyang itik, goyang pinguin, dan apapun yang dibilang goyangan cetar-badai, hingga sampailah mereka ke sungai Weser, dimana semuanya, ditenggelamkan dan binasa!