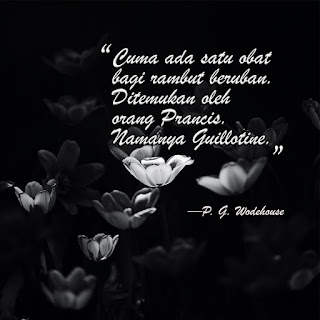Kutipan & Rujukan:“'Pada pukul lima pagi, sang Ratu masih menulis surat perpisahannya,' Monsieur de France membuka ceritanya," berkata Rembulan saat ia tiba, usai mengucapkan Basmalah dan Salam. "Sang Monsieur meneruskan, 'Di Paris, di seputaran delapan empat puluh, genderang ditabuh. Sebelumnya, pukul tujuh, seluruh angkatan bersenjata ibu kota, sedang beraksi; meriam diisi, menjaga jembatan; prajurit infanteri dengan bayonet, berbaris di jalan-jalan, dan ada skuadron kavaleri yang memperkuat mereka—pameran besar tentara melawan seorang wanita kesepian, yang dirinya sendiri, tak berharap apapun selain Kebersudahan. Cukup sering, para pengguna kekuasaan, lebih takut pada korbannya, ketimbang sang korban itu sendiri, terhadap para pengguna kekuasaan.Pada pukul tujuh, pelayan dapur sipir penjara, diam-diam masuk ke dalam sel sang Ratu. Di atas meja, dua lilin parafin, masih menyala; di sudut, sebuah bayang berwaspada, duduk gendarme—perwira polisi bersenjata di Prancis—yang sedang bertugas. Pada awalnya, Rosalie tak melihat sang tahanan, lantas, saat ia melihat lebih dekat, ia memperhatikan bahwa sang Ratu, berpakaian lengkap dan mengenakan gaun janda hitamnya, sedang berbaring di tempat tidur. Tak terlelap, cuma penat, dan lelah lantaran pendarahan berulang.Sang gadis dusun, sangat bersimpati pada Ratu yang ini, yang bakal dihukum mati, 'Madame,' katanya, mendekat ke tempat tidur, 'Engkau belum makan apapun, kemarin malam, dan hampir tak menelan apapun, di siang hari. Apa yang dapat kubawakan, pagi ini?''Nak, aku tak menginginkan apa-apa lagi, sebab bagiku, segalanya t'lah berakhir,' jawab sang Ratu, tanpa beringsut duduk.Ketika sang gadis, sekali lagi mendesaknya, agar memakan sup yang telah disiapkan khusus baginya, ia menjawab, 'Baiklah, Rosalie, bawakanlah supnya untukku.' Ia menelan beberapa sendok, dan kemudian sang pelayan, mulai membantunya membuka pakaian. Sang Ratu, Marie Antoinette, tak diperbolehkan naik ke pengaram, dalam pakaian berkabung yang dikenakannya, saat diadili di hadapan Pengadilan Revolusi, sebab pihak berwenang, takut gaun sang janda, bisa dianggap provokatif oleh para khalayak. Duh, apa pentingnya sih, gaun tersebut sekarang? Ia tak keberatan, dan memutuskan mengenakan gaun-putih bersahaja.Akan tetapi, bahkan kesempatan bontot inipun, penghinaan terakhir, telah ia telan. Selama berhari-hari, kini, ia kehabisan darah, dan baju ganti yang ia kenakan, kotor olehnya. Punya kehendak alami menjelang kematiannya, dalam keadaan bersih, ia ingin mengenakan pakaian dalam yang baru, dan memohon kepada sang gendarme, agar menarik-diri selama beberapa menit. Namun sang polisi, setelah diberi perintah keras agar tak membiarkan dirinya hilang dari pandangannya, walau sejenak, mengatakan, ia tak punya pilihan lain selain menolak. Sang Ratu, karenanya, berjongkok di ruang sempit antara tempat tidur dan dinding, dan, kala ia mengubah posisinyanya, sang pelayan dapur berdiri di antara dirinya dan sang prawira, agar menyembunyikan keterpolosannya. Lantas, pakaian dalam yang telah berlumuran darah ini, mau diapain coba? Ia malu memikirkan, meninggalkan linen kotornya, yang bakal diintai para khalayak, yang, dalam beberapa jam, kelak memasuki selnya, memeriksa segala yang ia tinggalkan di sana; maka, dengan cepat, ia menggulungnya menjadi buntelan kecil, memasukkannya ke dalam sebuah celah, bagian belakang perapian.Kemudian, ia berpakaian dengan sangat cermat. Lebih dari setahun sejak ia menginjakkan kaki di jalanan, lebih dari setahun sejak ia memandang lepas ke langit. Kemajuan terakhir ini, harus menyaksikannya berpakaian sopan dan bersih. Hasrat yang menjiwai dirinya, bukan lagi kesombongan feminin, melainkan, rasa-bermartabat, selama satu jam bersejarah. Ia dengan jeli merapikan gaun putihnya, membalut lehernya dengan kain muslin, dan mengenakan sepatu terbaiknya. Rambut putihnya, ia tutupi dengan topi bersayap dua.Pada pukul delapan, terdengar ketukan di pintu. Bukan, itu bukan sang algojo, melainkan cuma pembawa berita sang algojo, seorang pendeta, salah seorang dari, mereka yang telah mengambil sumpah setia kepada Republik. Sang Ratu, tak mengakui pendeta selain non-juror, dan ia menafikan dengan sopan, mengakui dosa-dosanya dan memohon ampunan dari orang yang ia anggap murtad. Saat sang pendeta bertanya haruskah ia menyertainya, dalam perjalanan terakhirnya, sang Ratu menjawab, cuek, 'Sa' karebmu!'Ketidakpedulian yang tampak ini, dinding pertahanan dimana Marie Antoinette, sedang mempersiapkan Ketegarannya demi perjalanan ke pengaram, tempat dimana sang Guillotine, bertitah. Ketika, pada pukul sepuluh, Sanson—yang sebenarnya Charles Henri, dikenal sebagai 'the Great Henri,' putra Chevalier Charles-Henri Sanson de Longval—sang algojo, seorang pemuda bertubuh bongsor, masuk untuk memotong rambutnya, ia tak keberatan dan tak memberikan perlawanan, tak pula dikala sang algojo mengikat kedua lengannya ke belakang punggungnya. Ia telah maklum, HIDUP, takkan dapat lagi diselamatkan, namun KEHORMATAN, masih bisa. Dan Kehormatannya menuntut, bahwa, tak boleh ada tanda-tanda kedaifan. Semata KEISTIQAMAHAN, yang dibutuhkan, demi menunjukkan kepada semua yang peduli, bagaimana cara putri Maria Theresa, hilang-hayat.Seputaran pukul sebelas, gerbang Conciergerie dibuka. Di luar tegak-berdiri tumbril—nama yang diplesetkan, sejenis gerobak tradisional, dimana, ditarik oleh kuda yang kekar, para korban Pengadilan Revolusi diarak menuju eksekusi, Louis XVI, sungguh, telah membuat kemajuan kerajaannya menuju kematian pada waktunya, ditempatkan di kereta istananya yang tertutup, dilindungi oleh dinding kaca dari penghinaan terburuk, dari keingintahuan yang paling buruk, dari pameran kebencian rakyat yang paling kasar dan buruk. Sejak saat itu, Republik telah membuat kemajuan pesat. Harus ada Kesetaraan, bahkanpun dalam perjalanan menuju sang Guillotine. Tiada alasan mengapa seorang mantan Ratu, harus menerima ajal dengan lebih nyaman dibanding warga negara lain, dan kereta bancilah, yang cukup baik bagi sang Janda dari Dinasti Capetian ini! Tempat duduknya, papan telanjang, yang dipasang di bagian atas. Danton, Robespierre, Fouquier-Tinville, Hébert—semuanya yang sekarang mengantarkan Marie Antoinette menuju kematiannya—akan menempuh perjalanan terakhir mereka, dengan duduk di atas kayu-alot yang sama; dan yang terhukum hari ini, sekadar beberapa tahap di depan para hakimnya. Bulan depan, Madame Roland, bulan berikutnya, Madame Dubarry, bakalan menempuh arteri yang sama.Yang pertama muncul dari pintu gelap Conciergerie itu, beberapa perwira, yang diikuti oleh kompi tentara dengan senapan terkokang. Setelah itu, dengan tenang, dan dengan langkah mantap, terlihat Marie Antoinette, Sanson, sang algojo, memeganginya dengan tali panjang, ujung tali yang ia gunakan mengikat lengannya, di balik punggungnya; mengekangnya, seolah ada bahaya bahwa korbannya, kendati dikelilingi ratusan lelaki bersenjata, masih mampu melepaskan diri darinya. Beberapa pengamat, terlepas dari diri mereka sendiri, terkejut dengan penghinaan yang tak terduga dan tak penting ini. Tak satupun dari teriakan sinis yang lazim ini, diangkat. Tiada kata yang terucap, saat sang Ratu berjalan menuju tumbril. Di sana, Sanson membantunya masuk, Girard, sang pendeta, yang tak mengenakan jubah, tapi mengenakan pakaian sipil, duduk di sampingnya. Sang algojo, dengan wajah kaku, tetap berdiri di sepanjang perjalanan, masih dengan dawai di tangannya. Dengan keprihatinan yang tak lebih dari apa yang dilakukan Charon, yang mengangkut jiwa-jiwa yang mati, melintasi Styx, yang setiap hari, mengantarkan kargo terkutuknya, ke pantai lain kehidupan. Akan tetapi, pada kesempatan ini, selama perjalanan, ia dan asistennya, memegang topi tiga sudut, diletakkan di bawah genggaman mereka, seolah-olah, dengan token kehormatan yang tak biasa ini, mereka memohon ampunan dari wanita tak berdaya, yang 'kan mereka pancung diatas aram-aram.Tumbril berderak perlahan di atas trotoar batu. Banyak waktu telah diberikan bagi perjalanan, lantaran semua minta diberi kesempatan, memanjakan mata mereka dengan tontonan yang tak-biasa. Di kursi keras, sang Ratu, terhentak oleh setiap gerakan gerobak yang dibuat secara kasar, tapi, wajahnya yang pucat, tak terganggu, menatap hampa dengan mata berbingkai merahnya, Marie Antoinette tak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, tiada gejala bahwa ia peduli pada kerumunan kepo, yang telah berkumpul demi melihat kepergiannya, menuju ke azabnya. Sia-sia musuh-musuhnya yang terganas, mencoba mendeteksi, sebuah tanda kelemahan. Tiada yang bisa menggoyahkan ketenangannya; bahkan ketika, saat ia melewati gereja Saint Roch, para wanita yang berkumpul di sana, menyerangnya dengan teriakan cemoohan; bahkan selagi Grammont sang aktor, yang ingin memeriahkan adegan suram, mengenakan seragam Garda Nasionalnya, naik beberapa langkah di samping kereta maut, mengayunkan pedangnya dan berseru, 'Inilah, Antoinette yang masyhur! Ia telah berakhir, guys!' Sang Ratu, seakan tak mendengar atau melihat. Teriakan keji di jalan, tak meninggalkan kesan pada gerbongnya, sorot-mata biadab, tiada kesan di matanya, lantaran pahitnya kematian, telah berlalu. Bahkan Hebert, harus mengakui, keesokan harinya, dalam 'Pére Duchesne,' 'Sang perempuan-jalang, selebihnya, berani dan lancang jelang titik-akhir.'Di sudut Rue Saint-Honoré, dimana Café de la Régence kini berdiri, seorang lelaki berdiri menunggu, sebuah pukal seniman di satu tangan dan pensil di tangan lainnya. Ia, Louis David, salah seorang pengecut terbesar, tetapi juga salah seorang pelukis terhebat di zamannya. Di antara para penyembur paling keras saat Revolusi sedang diteriakkan, ia berbhakti pada orang-orang berkuasa sepanjang mereka perkasa, mengabaikan mereka di saat-saat bahaya. Ia melukis Marat di kandang kematian. Saat Thermidor Kedelapan tiba, ia secara emosional menuturkan pada Rabespierre 'minum secawan bersamanya, sampai ampas,' namun hari berikutnya, bahwa ampas yang fatal itu, rasa dahaga akan kepahlawanan, telah dipadamkan; ia memutuskan berdiam di rumah, dan dengan demikian menyelamatkan dirinya dari sang Guillotine. Tiada yang mampu lebih pahit mencela para tiran dibanding dirinya, selama Revolusi, namun ia bakal menjadi salah seorang, yang pertama kali menempelkan dirinya, pada bertambahnya harta-kekayaan Diktator baru; dan pada waktunya, saat ia membuat goresan penobatan Napoleon, dan untuk layanan ini, beroleh gelar Baron, ia menunjukkan betapa asli kebenciannya, terhadap para Aristokrat. Spesimen khas dari mereka yang menjilat sepatu bot para penguasa, selalu siap menyanjung yang sukses, tetapi keji terhadap yang kalah, ia siap melukis sang pemenang saat penobatan, dan yang kalah dalam perjalanan ke pengaram. Dari gejolak yang sama, yang sekarang membawa Marie Antoinette menuju takdirnya, Danton, yang tahu betapa hinanya jiwa lelaki itu, mendesiskan padanya seruan, 'Dirimu itu, seorang antek!' Namun meskipun ia makhluk yang tercela, kendatipun ia berjiwa seorang pelayan, ia memiliki mata dan tangan seorang seniman. Dalam sekejap, ia telah membuat sketsa sang Ratu saat ia lewat, rajahan keji yang menakjubkan, terbuat dari kehidupan dengan keterampilan yang jalang; lukisan seorang wanita, yang tua sebelum waktunya, tak lagi cantik, yang tersisa, cuma kebanggaan. Mulutnya terkatup angkuh; ekspresinya menunjukkan ketidakpedulian yang mendalam; dengan tangan terbelenggu di balik punggungnya, ia duduk tegak di kursi kayu tumbril, seolah ia duduk di atas Singgasana, Setiap garis wajahnya yang membatu, berbicara mengumbar kehinaan, dan posenya, sebuah resolusi yang tak terkalahkan. Penderitaan berubah menjadi pembangkangan, rasa-sakit bermetamorfosis menjadi energi, menyajikan wajahnya yang tersiksa, keagungan baru dan mengerikan. Bahkan kebencian, yang membuat gambar ini, tak dapat menyangkal martabat mengerikan, yang dengannya, Marie Antoinette menanggung rasa-malu, saat dihantarkan menuju tempat eksekusi.Place de la Révolution yang luuwaas banget, sekarang dikenal sebagai Place de la Concorde, dipadati oleh kerumunan. Puluhan ribu kaki berdiri di sana, sejak pagi hari, agar mereka tak melewatkan tontonan unik seorang Ratu, sebagaimana omongan kecut Hébert, 'dicukur oleh pisau cukur nasional.' Mereka terus menunggu di sana, berjam-jam. Agar menghabiskan waktu, seseorang menyapa neng geulis di sampingnya, tertawa dan bergosip, beli koran atau karikatur dari Mas Paijo yang lewat, memborong seblak, cimol, cilok, kerak-telor, bakso, de-el-el, yang penjajanya mirip seorang Vlogger atau Youtuber atau yang berpakaian a la Spiderman. Namun, kagak ada bakul-sate, soalnya, asapnya kemana-mana, dan bakalan dikejar Satpol-PP, ambyar deh acara pemancungan!Ada pula, yang mengibaskan halaman pamflet paling topikal, seperti 'Les adieux de la Reine à ses mignons et mignonnes' dan 'Grandes fureurs de la ci-devant Reine.' Di kompleks perumahan, ada bisik-bisik tetangga, kepala siapa yang kemungkinan akan lepas, esok atau lusa. Adegan akbar ini, layak membutuhkan sedikit kesabaran.Menjulang di atas kepala orang banyak, yang kepo dan bersemangat ini, terlihat satu-satunya benda tak bergerak di alun-alun luas, pertama-tama, the one and only, sang Guillotine. Bukanlah Joseph-Ignace Guillotin yang menemukan sang Guillotine, namanya cuma jadi eponim. Penemu sebenarnya, orang yang bernama Tobias Schmidt, bekerja pada seorang dokter raja, Antoine Louis. Dr. Guilotin itu, seorang dokter, politikus, dan freemason Prancis, yang mengusulkan pada tanggal 10 Oktober 1789, penggunaan alat bagi pelaksanakan hukuman mati di Prancis, sebagai metode eksekusi, yang tak terlalu menyakitkan dibanding metode yang ada.Pada tanggal 9 Oktober 1789, Majelis Nasional, sebagai akibat dari eksodus tragis Pengadilan Versailles, memutuskan, memindahkan diri ke Paris, dan Dr. Guillotin, sebagai salah satu perwakilan dari kota tersebut, berpikir perlu mempersiapkan bagi dirinya sendiri, penerimaan yang baik dari konstituennya, dan pada hari itu pula, ia menyampaikan usulan, dan pada tanggal 10 berikutnya, menghasilkan serangkaian proposisi berikut:— Kejahatan-kejahatan yang sejenis, harus dihukum dengan jenis hukuman yang sama, seberapapun pangkat penjahatnya.— Dalam semua kasus (apapun kejahatannya) hukuman mati, harus dari jenis yang sama—yaitu, pemenggalan kepala—dan harus dieksekusi dengan mesin [Teffet d'un simple mecanisme]— dst ... dst ...Sang Guillotine yang tegak berkacak-pinggang, bagian atasnya dihubungkan oleh dua palang—jembatan kayu yang menghubungkan alam ini ke sarangnya. Di dekat puncak sana, berkilau di bawah sinar Mentari, Oktober yang dingin, palang yang siap dilepaskan, sebuah pisau yang baru diasah. Instrumen mengerikan ini, berdiri tajam dan jelas menjulang, dan para unggas, yang tak tahu apa-apa tentang makna jahatnya, melayang-layang di atasnya, berucap, 'Emang gue pikirin!'Di dekatnya, jauh lebih tinggi dari pintu gerbang kematian, berdiri patung Liberty yang besar, di atas fondasi yang pernah menjadi tugu Louis XV. Sosok yang duduk, dewi yang tak dapat didekati, kepalanya bermahkotakan topi Frigia, dan pedang keadilan di tangannya; ia duduk di sana, panik, Goddess of Liberty, bermimpi, bermimpi. Mata putihnya menatap kerumunan yang gelisah dan melintasi 'sang pembunuh manusiawi' ke jarak yang tak terlihat mata manusia. Ia tak melihat manusia sama sekali, baik hidup maupun mati mereka—dewi yang tak dapat dipahami dan dicintai selamanya, dengan mata batu yang bermimpi. Ia tak mendengar suara orang-orang yang memohon padanya; ia tak memperhatikan karangan bunga yang diletakkan di atas lututnya yang berbatu; ia tak menyaksikan darah yang membasahi bumi di bawah tubuhnya. Cita-cita abadi, alien di antara manusia, ia duduk diam menatap kehampaan yang jauh, merenungkan tujuannya yang tak tampak. Ia tak bertanya atau ingin tahu, perbuatan apa yang telah dilakukan, atas namanya.Lalu, terjadilah kegemparan di antara kerumunan, dan hening tiba-tiba. Keheningan ini, dipecahkan oleh pekikan biadab Rue Saint-Honoré. Satu skuadron kavaleri masuk Place, diikuti oleh tumbril, tempat duduk seorang wanita terikat, yang pernah menjadi Ratu Prancis; di belakangnya, berdiri Sanson, sang algojo. Maka, masih di alun-alun besar itu, derap kuda dan kisi-kisi roda, terdengar jelas. Ribuan penonton, dengan sedemikian ngeri, memandang korban yang pucat, yang nampak mengabaikan kehadiran mereka. Ia semata menunggu ujian terakhir. Dalam beberapa menit, kematian 'kan menjelang, diikuti oleh keabadian.Sang tumbril berhenti di samping aram-aram. Tanpa bantuan, 'dengan suasana yang lebih tenang dibanding saat meninggalkan penjara,' sang Ratu menaiki tangga kayu, menapakinya dengan ringan dengan sepatu satin hitam bertumit tinggi, seolah itulah tangga marmer di Versailles. Satu tatapan terakhir, ke atas, di atas kepala para penonton! Adakah ia, melalui kabut musim gugur, melihat Tuileries, dimana ia telah bermukim hampir tiga tahun dan telah mengalami penderitaan yang sangat menakutkan? Adakah ia, selama menit terakhir hidupnya, mengingat hari ketika kerumunan yang mirip dengan yang sekarang berkumpul, hanya berbeda dalam sikap dan pikiran, telah, di taman-taman Tuileries, menyatakan dirinya sebagai penerus takhta? Siapa yang tahu? Tiada yang pernah mempelajari pikiran akhir kematian. Puncak telah tiba, sang algojo dan asistennya, menangkap punggungnya, mendorongnya ke posisinya, berlutut, dengan tenggorokan di bagian bawah ronde; papan atas disesuaikan dengan bagian belakang lehernya; mereka menarik talinya; kilasan pisau yang jatuh; bunyi tumpul; dan, di dekat rambutnya, Sanson memungut kepala yang berdarah dan mengangkatnya tinggi-tinggi guna disoraki orang banyak. Mereka yang telah menahan napas selama setengah menit terakhir, sekarang berteriak 'Hidup Republik!' Kemudian para penonton buru-buru berhamburan. 'Parbleu, ini sudah pukul dua belas lewat seperempat, lebih dari waktu bagi déjeuner; kita harus cepat pulang.' Tak perlu kemana-mana! Esok, hari demi hari, selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, mereka yang menyukai panorama dan aroma darah, 'kan dapat berkumpul di Place de la Révolution, dan menyaksikan tragedi yang sama, berulang, ribuan kali lipat.'Monsieur de France terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca, dan setelah menyeka matanya, ia berkata, 'Sang algojo mendorong jasad itu, dengan kereta kecil, kepala sang Ratu disorongkan di antara kaki. Beberapa polisi tersisa menjaga pengaram. Tiada yang mempersoalkan, darah yang perlahan meresap ke tanah.Selain sang gendarmes, satu-satunya penonton yang tersisa di Place de la Révolution itu, Dewi Liberty, diam terpaku, galau, menatap seperti sebelumnya, ke cakrawala, menuju tujuannya yang tak menampak. Tentang kejadian pagi itu di alun-alun, ia tak menyimak dan tak mendengar apapun. Roman tak berias, mengabaikan kebiadaban dan kebodohan umat manusia, ia merenungkan cakrawala abadi. Ia tak tahu, atau tak ingin tahu, perbuatan yang dilakukan atas namanya. Pemakaman Madeleine, menjadi saksi bisu jasad Marie Antoinette, yang pernah menjadi Ratu Prancis.'"Rembulan menghela nafas, berkata, "Sungguh, setelah Revolusi pecah, sang Tiran tak bisa lepas dari sang Guillotine. Namun di balik Revolusi itu, banyak para pengecut, alias antek-antek sang Tiran, bersembunyi, dan kemudian, saat keadaan aman, mereka menciptakan makhluk saingan bagi sang Guillotine, Oligarki, sebuah keniscayaan, yang tak dapat disangkal oleh Demokrasi. Kelak, bila ada Revolusi berikutnya, saat dibawa ke hadapan pengadilan, akankah mereka berkilah, dengan mengutip kata-kata terakhir Marie Antoinette, yang dicatat sebagai, 'Pardonnez-moi, monsieur. Je ne l'ai pas fait exprès' atau 'Maafkan Tuan. Aku tak sengaja melakukannya,' setelah tanpa terencana, menginjak sepatu algojonya? Wallahu a'lam."
- Stefan Zweig, Marie Antoinette—The Portrait of an Average Woman, Cassel nd Company, Ltd.
- John Wilson Croker, The History of the Guillotine, John Murray