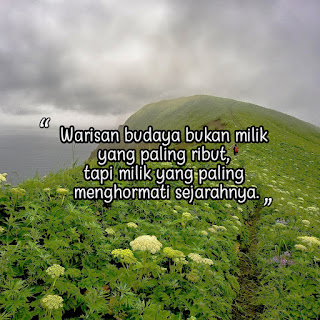Bayangin begini: lomba perahu khas Riau yang udah diwarisin turun-temurun, dilombain setiap tahun dengan sorak sorai rakyat, mendadak muncul di brosur pariwisata negara sebelah—dengan nama yang dipelintir dikit dan klaim "warisan budaya kami".Tradisi Pacu Jalur dari Riau—lomba dayung tradisional yang kental banget nuansa adat dan sejarah Melayu-nya—lagi-lagi diklaim sama Malaysia sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Ini bikin banyak warga Indonesia, terutama dari Riau, jadi geram. Soalnya bukan pertama kali juga kejadian kayak gini, dimana budaya yang udah lama dijaga dan dirawat turun-temurun malah mau "dipinjam" secara sepihak.Emang sih, Indonesia dan Malaysia punya akar budaya Melayu yang mirip. Tapi jangan sampai itu dijadiin alesan buat ngambil hak eksistensi budaya lokal yang jelas-jelas punya sejarah dan konteks tempat yang spesifik. Pacu Jalur itu udah masuk warisan budaya bukan benda Indonesia dan dirayakan tiap tahun kayak festival besar yang sakral dan semarak.Yang kita butuhin sekarang bukan klaim-klaiman atau adu gengsi budaya, tapi kerjasama budaya yang saling menghargai. Jangan sampai warisan nenek moyang kita jadi bahan rebutan negara, cuma karena pengakuan di kancah internasional.Tradisi Pacu Jalur itu udah ada sejak abad ke-17, muncul dari daerah Kuantan Singingi di Riau, Sumatra. Awalnya sih, perahu-perahu panjang yang super kece ini—bisa sampai 40 meter panjangnya, lho—dipakai buat transportasi di Sungai Batang Kuantan, terutama sama para datuk, penghulu, atau tokoh adat setempat. Tapi makin lama, aktivitas nyebrang sungai ini berubah jadi ajang lomba yang rame banget, apalagi pas momen-momen penting kayak perayaan hari besar Islam, panen raya, atau kunjungan tamu kehormatan.Lama-kelamaan, Pacu Jalur jadi semacam "olimpiade lokal" yang bawa semangat gotong royong, seni ukir perahu, dan harga diri kampung. Setiap desa bakal bikin jalur (perahu lomba) sendiri, dihias segila mungkin, lalu ngelatih pendayung mereka habis-habisan. Nggak cuma buat menang, tapi juga buat nunjukin solidaritas dan kebanggaan komunal. Sekarang, event ini rutin digelar tiap Agustus buat ngerayain Hari Kemerdekaan RI. Penontonnya bejibun, rame banget! Bahkan jadi simbol budaya maritim Riau yang bukan cuma soal olahraga, tapi juga soal spiritualitas, seni, dan identitas lokal yang kental banget.Pacu Jalur itu bukan sekadar lomba dayung biasa, tapi udah kayak festival budaya yang sarat makna, penuh simbol, dan spiritualitas. Tiap perahu—yang disebut jalur—dipahat dari satu pohon utuh, dan proses milih pohonnya pun kagak sembarangan. Biasanya dipilih pohon yang dianggep “punya jiwa”, karena dipercaya bisa bawa berkah dan kekuatan. Bagian depan perahunya sering banget dibentuk kayak naga, harimau, atau makhluk mitos lain. Bukan hiasan doang, itu simbol kekuatan, penjaga kampung, dan penghormatan ke leluhur.Kostum para pendayung juga nggak kalah keren. Biasanya mereka pakai seragam warna-warni yang nunjukin identitas kampung mereka. Ada yang motifnya klasik Melayu, ada juga yang modern tapi tetap lokal. Nah, si tukang pacu alias kapten perahu itu bukan cuma jago ngarahin jalur, tapi juga kayak semacam “pemimpin spiritual” tim. Doskilah yang mimpin teriakan semangat, jaga irama, bahkan “ngomong” ke jalur biar semangatnya bangkit. Sebelum lomba dimulai, ada ritual juga buat “membangunkan” roh perahu dan minta restu dari alam.Pesan utama dari Pacu Jalur tuh kuat banget: kerja sama itu kunci, budaya itu harus dijaga, dan alam itu harus dihormati. Anak muda yang ikut diingatkan bahwa kekuatan sejati itu bukan cuma soal otot atau menang, tapi soal kekompakan, penghargaan terhadap tradisi, dan rasa cinta pada akar budaya sendiri. Di zaman sekarang yang serba cepat dan digital, ini kayak alarm budaya yang nyentil, “Hei, jangan lupa siapa loe dan dari mana loe berasal!”Banyak banget kejadian dimana Malaysia ngaku-ngaku budaya yang jelas-jelas lahir dan besar di tanah Indonesia. Contohnya, Reog Ponorogo yang sakral banget dari Jawa Timur, batik yang udah diakui UNESCO sebagai warisan asli Indonesia, wayang kulit yang udah eksis sejak zaman kerajaan, sampai tarian Bali kayak Pendet yang penuh unsur spiritual. Belum lagi makanan legendaris kayak rendang dan tempe, yang udah jadi keseharian rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.Yang bikin banyak orang Indonesia naik darah itu bukan soal budaya serumpun atau mirip-mirip doang, tapi soal pengakuan sepihak. Malaysia kadang ngajuin ke UNESCO atau ngeklaim di event internasional seolah-olah itu asli mereka, padahal sejarah dan akar budayanya jelas-jelas dari Nusantara. Ini bukan cuma perkara “salah paham budaya”, tapi udah kayak perebutan hak siar sejarah. Rasanya tuh kayak loe punya karya, terus tetangga ngaku itu bikinan doski, dan doi yang dapet pujian duluan.Makanya penting banget buat anak muda Indonesia buat ngejaga, ngenalin, dan ngebanggain budaya sendiri. Soalnya kalau kita cuek, bisa-bisa warisan nenek moyang kita malah diklaim negara lain. Budaya itu bukan sekadar warisan, tapi juga identitas dan harga diri bangsa!
Guna mencegah budaya asli Indonesia diklaim negara lain, rakyat Indonesia harus kompak dan kreatif dalam merawat dan memamerkan budayanya sendiri—bukan sekadar sebagai tontonan tahunan pas 17-an, tapi sebagai bagian hidup sehari-hari yang bikin bangga. Jangan cuma nunggu pemerintah daftarin ke UNESCO; masyarakat juga bisa bikin konten, ngajar ke anak-anak muda, atau bahkan pake baju adat ke acara nikahan! Yang penting, budaya ini nggak cuma jadi pajangan, tapi jadi napas hidup. Dan semua itu harus tetap selaras ama Pancasila—khususnya soal keberagaman yang bersatu, saling menghormati, dan berkeadaban. Jadi, budaya kita bukan cuma eksis, tapi juga relevan dan keren di mata dunia, tanpa bikin kita jadi nyinyir atau defensif sama budaya orang lain.Salah satu langkah penting yang bisa dilakukan rakyat Indonesia biar budaya kita nggak diklaim negara lain adalah memperkuat “melek budaya” dari level akar rumput. Artinya, anak-anak muda harus paham asal-usul dan makna di balik budaya daerah mereka. Dari sistem matrilineal Minangkabau, kisah pewayangan Jawa, sesajen di pura Bali, sampai mahkota bulu khas Papua—semua itu bukan sekadar tontonan, tapi ekspresi hidup dari identitas bangsa. Kalau orang udah kenal akarnya, mereka bakal lebih siap ngebela budaya sendiri kalau ada yang coba ngaku-ngaku.
Tapi inget, ngerawat budaya itu bukan berarti harus anti-modern. Justru budaya harus bisa ngeblend sama perkembangan zaman. Contohnya, batik bisa diolah jadi fashion streetwear, gamelan dikolaborasiin sama musik elektronik, atau cerita rakyat dijadikan komik keren. Dengan cara ini, budaya jadi relevan buat generasi sekarang, dan susah buat diklaim orang lain karena kita udah duluan ngebanggainnya.
Tentu aja, semua ini harus dijalankan dengan tetap menghormati Pancasila—terutama sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini bukan soal agama tertentu, tapi soal kesadaran bahwa nilai spiritual itu penting banget dalam kehidupan budaya kita. Jadi, saat ngerayain tradisi atau bikin pertunjukan adat, harus tetap sensitif sama keharmonisan antarumat beragama. Jangan sampai budaya dijadikan dalih buat takhayul yang menyesatkan.
Menghormati sila pertama juga berarti jangan sampai upaya melestarikan budaya malah memicu konflik lama soal suku atau agama. Indonesia itu kuat justru karena keberagaman yang bersatu. Jadi, ketika kita menghidupkan kembali seni dan budaya daerah, narasi yang dibangun juga seyogyanya inklusif—yang ngerangkul seluruh kalangan dari Sabang sampai Merauke.
Dari sisi kebijakan, penting banget ada kolaborasi antara masyarakat lokal, akademisi, dan pemerintah. Pendokumentasian budaya, digitalisasi arsip, dan kurikulum pendidikan harus sejalan supaya tercipta ekosistem yang mendukung budaya Indonesia terus hidup dan dilestarikan. Bahkan diplomasi budaya juga perlu—dari kedutaan, promosi pariwisata, sampai pertukaran budaya biar dunia tahu, budaya ini milik siapa.
Saatnya bercermin. Kita bilang budaya itu “tak ternilai,” tapi nawar pengrajin sampai habis-habisan. Kita ingin yang otentik, tapi nontonnya reality show Korea. Kita ribut tari kita diklaim, tapi ke acara adat aja paling banter buat foto OOTD.
Coba bayangin kalau kita nggak nunggu dicuri dulu baru bangga. Bayangin kalau Pacu Jalur viral bukan karena hampir diklaim, tapi karena kita rawat sendiri tiap hari. Karena anak-anak bikin miniatur perahu. Karena tiap Agustus, ada lomba serupa di berbagai daerah.
Tapi nyatanya, kita baru nyari budaya kita setelah sirenenya bunyi. Kita kirim surat ke UNESCO kayak orang panik yang baru sadar anaknya ketinggalan di mall.
Untungnya, budaya itu nggak pendendam. Doi sabar. Doi nunggu. Doi ngasih kesempatan kedua. Yang doski minta cuma satu: jangan diperlakukan kayak barang antik. Perlakukan doi kayak keluarga—dirawat, disapa, diajak jalan-jalan sesekali.
Menjaga budaya itu soal cinta—bukan cuma takut diklaim, tapi karena kita beneran sayang dan bangga sama warisan leluhur. Kalau rasa cinta itu hadir dalam keseharian, maka budaya Indonesia bakal terus hidup. Dan di situ jualah kita ngebuktiin bahwa Pancasila bukan sekadar jargon politik, tapi cara hidup yang nyata: deket dengan Allah, hormat ke sesama, dan cinta tanah air lewat budaya yang hidup dan menghidupi.
Kalau budaya itu ibarat pasangan, maka kita tuh tipe yang cuek bebek dan sibuk sendiri, lalu ngamuk pas doi dipacarin orang. Kita marah bukan karena cinta, tapi karena gengsi. Jadi sebelum kita kehilangan lebih banyak, mungkin saatnya kita deketin lagi warisan leluhur—bukan sekadar buat konten patriotik dadakan, tapi biar budaya kita tahu, "Tenang, gua kagak bakalan cuekin loe lagi."