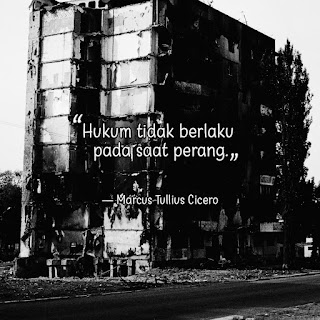[Bagian 3]Menjelang Perang Dunia Pertama tahun 1914, para pemimpin Eropa kayak lagi main “telepon rusak”—semua saling kirim sinyal, tapi gak ada yang bener-bener ngerti maksudnya. Ada satu cerita lucu tapi nyesek tentang Kaiser Wilhelm II, bos besar Jerman saat itu. Pas doski sadar dunia udah kebakar, doi malah nulis di pinggir dokumen perang: “Kalau saja ada yang kasih tahu aku lebih awal!”Kebayang gak? Seorang kaisar, yang mestinya paling tahu segalanya, malah kayak anak magang yang gak dapet briefing. Tapi di situlah letak poin pentingnya: perang itu sering banget bukan karena orang mau, tapi karena mereka salah paham, gengsi mundur, atau udah terjebak janji ke aliansi kayak lagi janji traktiran ke temen satu tongkrongan.Dan dari sana, dunia masuk ke lubang hitam perang, kayak sleepwalker yang kelihatan santai di luar, tapi gak nyadar bentar lagi nabrak tembok sejarah. Jadi ya, kadang perang itu bukan hasil rencana jahat—tapi hasil kombo antara ego, miskom, dan kagak ada yang berani bilang, “Stop, bro. Udahan dulu.”Sejak dulu, perang itu udah kayak mantan toxic—selalu balik lagi dalam hidup umat manusia. Dari zaman Sumeria lawan Elam ribuan tahun sebelum Masehi, sampai Sparta ribut sama Athena kayak dua fandom K-pop adu siapa paling OG, manusia nggak pernah bosen adu kekuasaan dan wilayah.Romawi keliling dunia sambil ngibarin bendera ego, Mongol sweeping benua kayak live action ‘Game of Thrones’, ekspansi Islam juga ikut merombak peta dan budaya. Pas zaman Crusade? Wah, agama dijadiin alesan, tapi jangan salah—ambisi kekuasaan tetep main di belakang layar. Lalu muncullah Napoleon, si pendek dengan mimpi gede yang bikin Eropa kayak panggung konser penuh asap meriam.Lompat ke abad 20, datang dua episode utama: Perang Dunia I dan II. Ini bukan sekadar perang, tapi seperti festival horor dengan teknologi canggih: tank, gas beracun, nuklir. Dunia ikut nonton... dan ikutan rusak. Lalu era Cold War muncul: Amerika dan Soviet gak adu jotos langsung, tapi mereka ngatur "drama tempur" di panggung lain—Vietnam, Afghanistan, dan kawan-kawan.Dan sekarang? Masih ada: dari Irak sampai Ukraina, dunia modern masih doyan pake kekerasan kayak nggak punya opsi menu lain. Kalau sejarah itu guru, manusia jelas murid yang bandel banget—udah sering disuruh belajar dari masa lalu, tapi masih aja ngulang kesalahan yang sama.Perang bisa terjadi karena dunia kadang terlalu ribet buat diajak ngobrol baik-baik. Kadang negara pengen eksis, pengen nunjukin siapa paling kuat, atau cuma pengen dapet minyak, emas, atau lahan lebih banyak. Bisa juga karena dendam sejarah yang gak pernah kelar atau karena ideologi yang beda kayak mantan yang kagak move on. Kalau diplomasi udah mentok, ego jadi mode on, dan ujung-ujungnya ya... dor-doran. Bahkan di dalam negeri sendiri, bisa pecah perang saudara gara-gara ketimpangan, diskriminasi, atau negara yang udah gak bisa ngatur. Intinya, kalau ngomong udah nggak mempan, peluru yang bicara.Carl von Clausewitz dalam "On War"—ini semacam kitab suci buat jenderal dan politisi, bilang bahwa perang itu bukan sekadar tembak-tembakan, tapi kelanjutan politik yang udah nggak bisa diselesaikan dengan debat kusir. Jadi, begitu para elite bosen duduk di meja rapat, mereka mulai ngeluarin tank.
Dalam The Causes of War (Macmillan, 1973), Geoffrey Blainey bilang perang itu terjadi bukan karena negara A jahat dan negara B baik—tapi karena dua-duanya sama-sama salah kira. Bayangin dua influencer yang ribut di media sosial gara-gara saling ngira follower-nya paling banyak dan paling setia. Mereka ngelempar sindiran, saling pamer kekuatan, dan akhirnya... collab-nya batal, dramanya pecah!Menurut Blainey, perang muncul pas diplomasi udah kayak obrolan grup WA yang gagal paham—gak nyambung, ngambek, dan saling ngegas. Negara A kira bisa menang cepat, Negara B juga mikir gitu. Jadi mereka maju perang, padahal dasarnya cuma ilusi dan kepercayaan diri berlebihan.Blainey juga bilang, perang bukan soal ideologi muluk atau sistem ekonomi doang. Kadang cuma soal salah baca gesture: kayak loe mikir tetangga ngeliatin loe sinis, padahal doi lagi ngelamun. Di level negara, salah paham kayak gitu bisa jadi bencana besar.Intinya, menurut Blainey, perang itu kayak ribut gara-gara salah paham di TikTok—cuma skalanya global dan korbannya jutaan.Blainey ini ibaratnya bilang, "Udah deh, jangan mikir gampang-gampang soal perang!" Doi paling males ama penjelasan yang bilang perang itu cuma gara-gara satu hal doang.Doi nantang banget ide Marxis yang bilang perang itu pasti dari konflik kelas atau kapitalisme. Terus, doi juga nyinyir ama klaim liberal yang bilang kalau demokrasi atau perdagangan bisa otomatis nyegah perang. Buat Blainey, itu semua klise.Menurutnya, ketidakpastian itu bumbu utamanya. Para pemimpin itu seringkali kayak lagi judi, nekat perang pas mereka yakin perangnya bakal cepet kelar, bisa dimenangin, atau penting banget buat harga diri bangsa, atau buat balikin keseimbangan.Blainey ngasih tahu kita kalau di balik konflik itu ada kesalahan penilaian manusia, intelijen yang cacat, dan optimisme strategis yang kebablasan. Bukan cuma soal sistem ekonomi atau politik doang. So, jangan kebanyakan GR pas lagi tegang-tegangan ama negara tetangga—karena bisa-bisa yang loe pikir cuma main gertak, ternyata jadi duel beneran!"A History of Warfare" (1993) dari John Keegan, sejarawan militer Inggris yang jago banget, kayak mau bilang, "Udah deh, jangan mimpi perang itu indah atau heroik!" Doski justru bongkar kenyataan brutal perang di berbagai budaya dan abad.Keegan ini beda dari kebanyakan. Doi gak setuju ama Clausewitz yang bilang perang itu cuma kelanjutan dari politik. Buat Keegan, perang itu bukan hal yang alami dari politik.Sebaliknya, doski melihat perang sebagai 'ciptaan' budaya dan institusi yang terus berkembang seiring dengan masyarakat manusia. Jadi, perang itu bukan takdir, tapi sesuatu yang kita bentuk dan ubah sendiri seiring waktu."War in Human Civilization" (2006) dari Azar Gat ini ibaratnya kayak film dokumenter panjang yang ngebahas perang dari zaman batu sampai sekarang. Intinya, Gat bilang gini: "Motif perang itu dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja, Bro! Mau peradaban makin canggih juga, akar masalahnya tetep sama." Menurut Gat, ada tiga pemicu utama kenapa manusia dari dulu sampai sekarang doyan banget perang.Pertama, ada perebutan sumber daya—entah itu soal duit, lahan, atau apa pun. Gat bilang ini naluri dasar kita buat bertahan hidup dan berkembang. Mau itu rebutan tanah, air, jalur dagang, atau ladang minyak, dari dulu sampai sekarang negara atau kelompok pasti ribut kalau ada sumber daya penting yang terbatas. Meskipun ekonomi udah global dan perdagangan makin maju, perebutan kendali ini enggak bakal hilang, cuma ganti bentuk aja.Kedua, ada rasa takut sama musuh, atau siapa cepat dia dapat! Rasa takut ini kayak bayangan yang ngikutin politik kekuasaan. Negara sering perang bukan karena pengen, tapi karena takut duluan sama apa yang bakal dilakukan musuh kalau mereka enggak gerak. Ini yang namanya "dilema keamanan". Meskipun niatnya cuma jaga diri, bisa aja malah dianggap ancaman, terus jadi perang deh!Terakhir, ada kehormatan alias harga diri bangsa! Ini bukan cuma soal harga diri pribadi atau suku, tapi harga diri bangsa secara kolektif. Negara, kayak individu, enggak mau diremehin atau kelihatan lemah. Keinginan buat jaga gengsi atau balas dendam masa lalu sering banget jadi alasan perang, padahal kerugian materinya enggak seberapa. Kehormatan, dalam hal ini, bisa sekuat rasa takut atau ketamakan dalam nyetir negara buat perang.Azar Gat punya argumen yang jelas banget: perang itu bukan cuma "bug" atau error di sistem peradaban manusia. Justru, perang itu bagian dari "kode" atau DNA kita sendiri, warisan dari biologi evolusi dan konstruksi sosial yang udah kita bangun di atasnya.Dalam The Utility of Force (2005), Jenderal Rupert Smith bilang, "Lupakan perang gaya lama yang kek di film Saving Private Ryan." Zaman dimana negara adu kekuatan lewat tank, artileri berat, dan pasukan baris-berbaris udah lewat. Sekarang kita hidup di era yang doski sebut "perang di tengah masyarakat". Jadi, perang bukan lagi antara dua negara di lapangan luas, tapi di gang-gang sempit, kampung padat, atau kota-kota hancur kayak di Mosul, Sarajevo, atau Kabul—dimana warga sipil, tentara, dan milisi nyampur jadi satu.Menurut Smith, kemenangan lewat kekuatan militer brutal itu udah gak relevan. Perang modern lebih kayak sinetron politik yang kagak kelar-kelar, dengan plot twist, infiltrasi, dan permainan opini publik. Bukan cuma soal menang perang, tapi soal merebut simpati, mengatur narasi, dan bikin warga percaya siapa yang benar. Musuh bisa siapa aja—teroris, preman bersenjata, atau bahkan influencer yang nyebar hoaks.Dan yang bikin ribet, garis antara damai dan perang makin kabur. Tentara bisa lagi bagi bantuan makanan hari ini, lalu besok kena serangan granat di tempat yang sama. Smith bilang, tentara sekarang harus lebih pinter diplomasi daripada jago nembak. Sistem militer klasik, yang dirancang buat Perang Dunia II, udah nggak cocok dipakai buat konflik kayak ini.Perang zaman now udah jadi urusan total: bukan cuma tentara, tapi juga aktivis, jurnalis, diplomat, dan netizen Twitter. Kalau loe masih mikir perang itu soal menang atau kalah, loe ketinggalan zaman. Sekarang, perang itu soal siapa yang bisa bertahan dan punya narasi paling meyakinkan di tengah masyarakat yang tercerai-berai.Dalam The Better Angels of Our Nature (2011), buku yang tebal dan lumayan bikin mikir, Steven Pinker bilang, "Guys, dunia emang kelihatan kacau, tapi sebenarnya kita jauh lebih damai dibanding zaman nenek moyang kita." Menurut Pinker, sejarah panjang umat manusia bukan cuma cerita tentang perang dan penjajahan, tapi juga tentang gimana kekerasan pelan-pelan berkurang. Kok bisa? Karena munculnya institusi negara yang bisa ngatur dan menghukum, orang makin melek huruf dan bisa saling ngerti, perdagangan bikin kita saling butuh, dan empati—yes, rasa iba—makin kuat berkat nilai-nilai kemanusiaan.Dampaknya? Kalau kekerasan itu bukan takdir, tapi sesuatu yang bisa dikurangi lewat perubahan sosial, maka harapan buat dunia damai itu bukan mimpi. Ini semacam tamparan buat kita yang suka bilang, “Dunia makin rusak!” Padahal justru sebaliknya: dunia makin waras, cuma kita kebanyakan nonton berita buruk. Yang perlu kita rawat adalah hal-hal kayak pendidikan, demokrasi, hukum yang adil, dagang internasional, dan media yang nggak bikin panik—karena semua itu bikin kekerasan jadi nggak seksi lagi.Pinker ngajak kita mikir: mungkin kita masih lihat perang dan kekejaman, tapi secara garis besar, umat manusia lagi naik kelas moral. Kita makin bisa lihat orang yang beda ras, agama, atau negara sebagai sesama manusia. Dan itu luar biasa. Tapi damai itu nggak gratis, bro—harus dijaga, dipupuk, dan diperjuangkan terus. Soalnya, dunia damai bukanlah akhir cerita, tapi serial panjang yang harus terus kita perpanjang musimnya.Gagasan Pinker itu keren—optimis, bikin adem. Tapi sayangnya, gagasan doski gak selalu cocok di semua tempat dan semua waktu. Kayak teori idealis yang butuh panggung stabil buat bisa jalan. Kalau negaranya hancur, pemerintahnya bubar jalan, internet dipenuhi hoaks, dan rakyat hidup dalam ketimpangan, ya sorry to say, teori Pinker bisa mental.Contohnya? Lihat aja negara-negara yang gagal alias failed states, dimana nggak ada hukum yang ditegakkan, tentara jadi preman, dan hidup kayak film Mad Max. Atau saat krisis ekonomi parah, pandemi global, atau bencana iklim, manusia bisa berubah jadi survival mode—percaya sama yang paling keras suaranya, bukan yang paling waras. Dalam situasi gitu, empati dan rasionalitas kalah sama panik dan amarah.Dan jangan lupa, Pinker sering dikritik karena terlalu fokus sama kekerasan yang kelihatan—tembak-tembakan, perang, dan pembunuhan. Tapi gimana dengan kekerasan yang nggak berdarah tapi tetap nyakitin? Kayak rasisme sistemik, kemiskinan turun temurun, atau masyarakat adat yang terus disingkirkan dari tanahnya. Itu semua bentuk kekerasan juga, cuma bentuknya lebih halus dan sering dianggap "normal".Kendati Pinker ngasih harapan bahwa dunia makin damai, kita juga harus sadar: teori ini bisa gak berlaku kalau dunia lagi chaos, kalau institusi rusak, atau kalau masyarakat udah keburu terbelah kayak fans sinetron yang berantem di kolom komentar.
[Bagian 1]